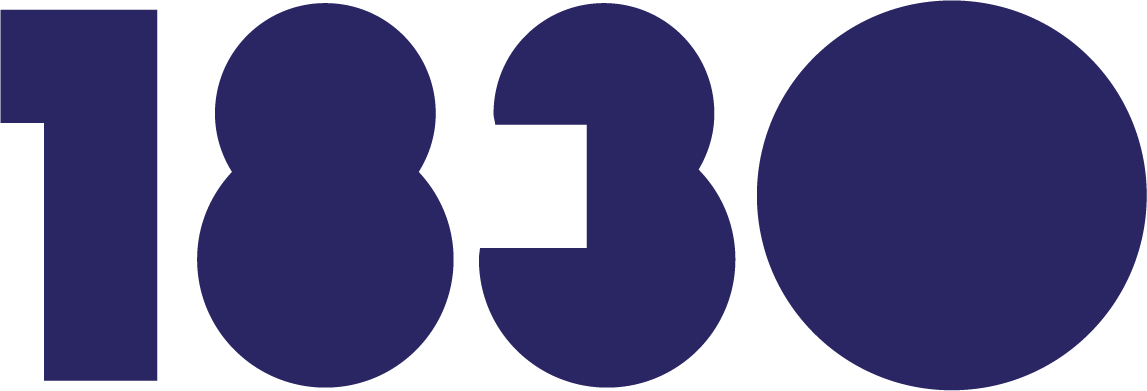Bab V.
Prajurit Wanita
Ratu Ageng (sekitar 1732–1803), permaisuri Sultan pertama Yogyakarta sekaligus pengasuh Pangeran Diponegoro, menjadi panglima pertama prajurit èstri (pengawal perempuan). Warisannya bertahan, karena banyak perempuan bangsawan kemudian ikut berjuang bersama Diponegoro dalam Perang Jawa melawan penjajahan Belanda.

Kerap sulit menemukan representasi budaya yang autentik tentang perempuan pejuang dan penguasa di Asia Tenggara. Padahal kisah-kisah ini sangat penting bagi bangsa muda yang tengah berupaya membentuk masa depannya dengan nilai inklusivitas, kesetaraan, dan akuntabilitas. Narasi tentang perempuan berpengaruh bukan hanya menghadirkan panutan, tetapi juga menawarkan refleksi kritis tentang bagaimana masyarakat dahulu merangkul keseimbangan dan berbagi kewenangan. Tantangan hari ini adalah bagaimana merekonstruksi kisah-kisah yang kian menghilang serta memulihkan peran perempuan dalam membangun peradaban agung seperti Jawa kuno.
—Melissa SunjayaKesan saya tentang perempuan Jawa dibentuk oleh dunia gaib Ratu Kidul, penguasa laut selatan. Melalui kehadirannya, saya merasakan daya perempuan-perempuan perkasa—sosok-sosok berkuasa yang dari namanya sendiri, per-empuan, merujuk pada pencapaian spiritual dan pemberdayaan. Dalam Jawa pra-kolonial, mereka hadir sebagai prajurit, pengrajin, sufi mistikus, peramal, tabib, dukun, hingga penempa bilah keris magis. Namun sebagian besar warisan ini telah lenyap. Bagaimana sejarah pemberdayaan semacam ini bisa terlupakan, dan bagaimana masa lalu Polinesia Jawa dapat terhapus begitu tuntas?
—Peter Carey
Apa gambaran paling populer tentang perempuan Jawa masa kini? Bagi banyak anak muda Indonesia saat ini, jawabannya lebih dipengaruhi oleh budaya pop Barat dan media massa daripada tokoh-tokoh pahlawan perempuan dalam sejarah. Lewat film, novel, dan platform sosial, arketipe yang berlaku menggambarkan perempuan Jawa sebagai sosok penurut, cantik, dan lemah lembut—sebuah stereotipe yang lebih menghargai kepasifan daripada kekuatan. Arketipe ini, yang muncul pada akhir abad ke-19 di bawah pengaruh kolonialisme, menyiratkan bahwa martabat dan femininitas ditentukan oleh diam dan ketiadaan.
Namun representasi sempit ini tidak mencerminkan kekayaan masa lalu Jawa. Pangeran Diponegoro, pemimpin karismatis Perang Jawa (1825–1830), lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga di mana perempuan berpengaruh memainkan peran penting dalam membentuk dunianya sejak kecil. Ia tumbuh di bawah asuhan dan bimbingan para tetua perempuan yang dihormati bukan hanya sebagai ibu dan pengasuh, tetapi juga sebagai strategis, pedagang, ahli bahasa, pejuang, dan mistikus. Pada masa pembentukannya, nilai-nilai matriarki dan patriarki hidup berdampingan dalam keadaan seimbang. Perempuan tidak terkungkung pada ranah domestik atau dibatasi oleh kelembutan bawaan; mereka justru terjalin erat dalam tatanan politik, budaya, dan spiritual kehidupan Jawa.
Kenyataan pra-kolonial ini penting untuk ditinjau kembali. Mengamati kehidupan Diponegoro melalui lensa feminis berarti memulihkan sejarah sebuah peradaban di mana daya besar perempuan bukanlah hal yang aneh atau luar biasa. Hal ini merupakan bagian dari tatanan kehidupan: sebuah masyarakat matriarki yang diwarisi dari masa lalu Polinesia di kepulauan ini. Memahami keseimbangan kekuasaan ini juga penting untuk menafsirkan sistem kepercayaan Jawa, seperti legenda abadi Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan.
Perempuan Perkasa dalam Dunia Diponegoro
Nenek buyut Diponegoro, Ratu Ageng, mewujudkan warisan ini. Sebagai permaisuri Sultan pertama Yogyakarta, ia bukan pasangan kerajaan yang pasif, melainkan seorang pemimpin militer pada awalnya. Ia memimpin prajurit èstri—pasukan perempuan yang terlatih dalam pertempuran, menunggang kuda, dan menggunakan karabin kavaleri—yang menjaga kadaton (istana dalam) pada malam hari. Disiplin dan kekuatan spiritual Ratu Ageng meninggalkan jejak mendalam pada cicitnya itu. Ia menggabungkan peran pengasuh sekaligus panglima, mewariskan keyakinan bahwa perempuan mampu memegang otoritas militer dan politik.
Dalam Perang Jawa, sekutu-sekutu perempuan Diponegoro bukanlah figuran simbolis, melainkan strategis yang menentukan. Di antaranya adalah Raden Ayu Serang, lebih dikenal sebagai Nyi Ageng Serang, keturunan wali besar penyebar Islam di Jawa bagian selatan-tengah, Sunan Kalijaga. Ditakuti Belanda karena keberaniannya di medan perang dan dihormati pengikut Jawa karena wawasannya sebagai seorang mistikus, ia memimpin pasukan dengan keahlian luar biasa. Pada awal September 1825, ia mengatur serangan malam yang menghancurkan satu kompi Belanda berjumlah 250 prajurit, menewaskan lebih dari setengahnya. Kepemimpinannya begitu menggentarkan hingga laporan Belanda menggambarkannya sebagai “seorang perempuan cerdas namun sangat ditakuti, yang unggul dalam tindakan kekejaman”. Kini, ia dikenang sebagai Pahlawan Nasional.
Mereka bukanlah tokoh-tokoh terisolasi. Catatan arsip menunjukkan bahwa perempuan Jawa berperan aktif dalam perdagangan, diplomasi, kehidupan beragama, dan politik istana hingga awal abad ke-19. Kekuatan mereka bukan hanya ditoleransi, tetapi dilembagakan. Korps pengawal perempuan ada di Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaran—mewujudkan pengakuan bahwa perempuan adalah pelindung sekaligus pejuang.

Keilahian Feminin dan Otoritas Sakral
The empowerment of Javanese women cannot be separated from the cosmological order. Myths of goddesses—Durga, Uma, and above all Ratu Kidul—illuminate the sacred dimension of female authority. Ratu Kidul, consort of kings since the founding of the Mataram dynasty, was seen as both destroyer and nurturer, death-bringer and fertility goddess. Her rituals in the palaces of Yogyakarta and Surakarta reinforced the idea that feminine power underpinned the legitimacy of rulers.
Sacred dances like the Bedoyo Ketawang invoked her presence through the bodies of nine high-born women. In these ceremonies, female dancers were not passive performers but living vessels for divine power. The mythic union of ruler and goddess reminded all that political authority was inseparable from feminine spiritual potency. For both Diponegoro and Nyi Ageng Serang, meditations in caves along the southern coast deepened their connection with this sacred feminine divinity, which guided them during the Java War.
Disrupsi Kolonial
Lalu, bagaimana keseimbangan ini bisa terkikis begitu cepat? Titik baliknya terjadi bersamaan dengan penaklukan kolonial. Pada tahun 1812, ketika Raffles memberlakukan perjanjian-perjanjian di istana-istana Jawa Tengah-Selatan, para penguasa dilarang memiliki pasukan tetap. Para pengawal perempuan, yang telah bertempur dengan gagah berani selama serangan Inggris di Yogyakarta tahun itu, dibubarkan. Meskipun sebagian dari mereka kemudian bergabung dalam pasukan Diponegoro, basis kelembagaan mereka telah hancur.
Pada saat yang sama, budaya kolonial Belanda memperkenalkan stereotip baru. Novel-novel akhir abad ke-19 karya penulis Eropa seperti Louis Couperus menyebarkan mitos tentang “Jawa yang lembut” dan “istri bupati yang ayu dan penurut” dalam roman tersohor De stille kracht (Kekuatan Diam, 1900)—gambaran perempuan yang tenang dan patuh, sangat jauh dari sosok ratu, prajurit, dan mistikus perempuan tangguh dalam sejarah Jawa. Narasi orientalis ini mengeksotiskan perempuan Jawa sebagai sensual dan tunduk, sekaligus menghapus peran historis mereka sebagai subjek yang berdaya.
Menjelang akhir masa kolonial, peran perempuan semakin dibatasi pada ranah domestik. Tokoh-tokoh seperti Kartini dan Dewi Sartika, yang memperjuangkan pendidikan dan reformasi, lahir dari konteks di mana ruang gerak perempuan telah dipangkas secara sistematis. Tidak seperti para bangsawan perempuan di sekitar Diponegoro, mereka hidup dalam dunia yang secara sistematis menutup akses bagi perempuan terhadap politik, kehidupan militer, maupun kepemimpinan intelektual.
Memulihkan Keseimbangan yang Hilang
Sejarah pra-kolonial perempuan Jawa menantang kita untuk memikirkan ulang feminisme di Asia Tenggara. Sering kali dipandang sebagai ideologi modern yang diimpor, feminisme sesungguhnya memiliki akar yang dalam di nusantara. Keseimbangan kekuatan laki-laki dan perempuan—yang tampak dalam politik, sistem kepercayaan, dan struktur sosial—telah menjadi bagian dari peradaban Jawa jauh sebelum kolonialisme Eropa. Masalahnya bukan karena feminisme tidak pernah ada, melainkan karena ia sengaja dihapus.
Saat ini, perempuan muda masih sering ditanya, “Kapan menikah?” atau “Kapan punya anak?”, tetapi penting diingat bahwa ekspektasi semacam ini bukanlah tradisi abadi. Hal ini tersebut warisan konstruksi kolonial yang sengaja mengecilkan peran perempuan. Jawa pra-kolonial menunjukkan kepada kita bahwa peran gender bisa sangat berbeda—bahwa perempuan dapat menjadi prajurit, strategis, mistikus, bahkan penguasa tanpa harus mengorbankan martabatnya sebagai perempuan.
Seperti yang diingatkan Yuval Noah Harari, alasan terbaik untuk mempelajari sejarah bukanlah untuk meramal masa depan, melainkan untuk membebaskan diri dari masa lalu dan membayangkan takdir-takdir alternatif. Mendekolonisasi pemahaman kita tentang gender menuntut pemulihan ingatan akan perempuan-perempuan perkasa ini serta penegasan kembali posisi mereka yang semestinya dalam sejarah kita.
Dengan meninjau kembali kehidupan Diponegoro melalui perspektif feminis, kita tidak hanya melihat kepahlawanan sang pangeran, tetapi juga para perempuan luar biasa yang membentuk dunianya. Mereka mengingatkan kita bahwa keseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan bukanlah mimpi utopis, melainkan kenyataan yang ada di Jawa dua abad yang lalu dan sangat mungkin dihidupkan kembali.